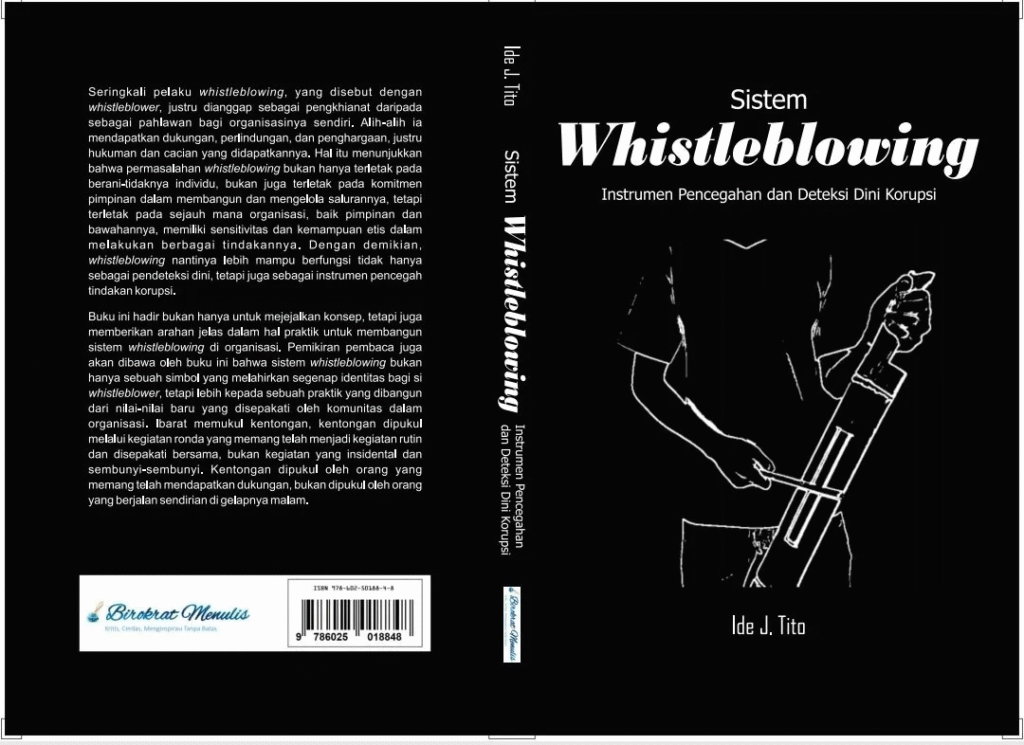
Faktor – faktor yang mempengaruhi keputusan whistleblowing dapat dibagi menjadi tiga kategori: karakteristik whistleblower atau variabel personal, karakteristik kontekstual atau variable situasional dan karakteristik organisasional.
Karakteristik personal merupakan faktor yang bersumber dari seorang whistleblower potensial. Variabel situasional merupakan faktor yang bersumber dari karakter pelanggaran itu sendiri, pelaku pelanggaran dan karakter penerima informasi whistleblowing. Variabel organisasional tercermin dari karakter organisasi dimana kejadian pelanggaran terjadi (Near & Miceli, 1995; Miceli et al, 2008; Mesmer-Magnus & Viswesvaran, 2005).
Karakter personal yang mempengaruhi keputusan whistleblowing yang dibahas dalam segmen ini adalah
- usia,
- masa kerja,
- status,
- jabatan,
- tingkat pendidikan,
- jenis kelamin,
- penilaian etis (ethical judgment), dan
- religiusitas.
Beberapa faktor lain yang diluar cakupan antara lain adalah kepribadian, ras, afektivitas, lokus pengendalian dan harga diri dan nilai- nilai kehidupan misalnya relativisme, idealisme dan, individualisme.
Usia dan masa kerja
Keterkaitan usia dan masa kerja terhadap perilaku whistleblowing dapat bersifat positif maupun negatif, inkonsisten dan tidak signifikan. Pegawai muda (junior) lebih jarang menjumpai pelanggaran dan lebih rentan terhadap retaliasi dan di-kambing hitam-kan dibandingkan dengan pegawai yang lebih tua sehingga kemungkinan ber-whistleblowing juga lebih kecil.
Namun demikian, kelompok pegawai kategori muda tersebut mungkin juga kurang mempunyai kepentingan terhadap kariernya di organisasi sehingga lebih tinggi kecenderungan untuk ber-whistleblowing.
Status pangkat dan jabatan whistleblower
Tingkat jabatan, status professional atau status manajerial mencerminkan tingkat kewenangan dan jarak kekuasaan (power distance) yaitu ukuran jarak antara seorang whistleblower potensial dan pelaku pelanggaran. Jarak kekuasaan ini dapat mempengaruhi keputusan whistleblowing secara positif dimana semakin tinggi jabatan semakin tinggi kecenderungan untuk ber-whistleblowing. Kelompok pegawai yang menduduki jabatan manajerial berkesempatan untuk mengetahui adanya pelanggaran sehingga lebih tinggi kemungkinan untuk ber-whistleblowing melalui saluran internal untuk mencegah publikasi yang dapat berdampak buruk bagi organisasi (Miceli et al, 2008; Miethe, 1999).
Pejabat tinggi juga pada umumnya mempunyai kewajiban formal dalam uraian jabatannya untuk melaporkan adanya pelanggaran (Rothwell & Baldwin, 2006). Selain itu, pejabat lapisan atas lebih berani menghadapi ancaman retaliasi (Keenan, 1990) dan mempunyai kapabilitas lebih untuk menilai tingkat kesalahan dan tingkat keseriusan suatu pelanggaran serta dapat lebih leluasa mengakses bukti adanya pelanggaran sehingga intensi whistleblowing-nya lebih tinggi.
Tingkat pendidikan
Pegawai yang berpendidikan tinggi dinilai lebih menyadari hak dan kewajiban hukum terkait whistleblowing dan hak untuk dilindungi dari retaliasi. Pegawai tersebut juga lebih dapat mencari pekerjaan lain sehingga ancaman pemecatan kurang ditakuti. Dengan demikian, pegawai berpendidikan tinggi lebih mungkin melakukan whistleblowing (Miethe, 1999)
Jenis kelamin
Jenis kelamin merupakan faktor yang tidak signifikan mempengaruhi keputusan whistleblowing (Rothschild dan Miethe, 1999; Dworkin dan Baucus, 1998). Namun demikian, kemungkinan ber-whistleblowing pegawai pria dapat lebih tinggi karena laki-laki cenderung menduduki jabatan yang lebih tinggi sehingga lebih dapat mengetahui adanya pelanggaran.
Selain itu pegawai laki-laki cenderung menjadi anggota asosiasi professional dimana perilaku whistleblowing menjadi bagian dari kode etik dan laki-laki pada umumnya mempunyai harga tinggi dan inisiatif yang lebih tinggi sedangkan perempuan cenderung mengikuti atau patuh dengan pendapat mayoritas. (Kaplan et al., 2009; Miceli & Near, 1992; Vadera, et al, 2009).
Penilaian etis (ethical judgment)
Penilaian etis didefinisikan sebagai proses meyakini bahwa suatu alternatif keputusan adalah keputusan yang paling etis (Hunt & Vitell, 1986) atau proses untuk menentukan, dalam sitausi tertentu, suatu keputusan adalah secara moral benar dan keputusan lainnya secara moral salah (Rest, 1986). Penilaian etis juga merupakan evaluasi personal mengenai seberapa etis atau seberapa tidak etis suatu perilaku atau keputusan diantara satu atau lebih pilihan lainnya dengan mengacu pada tujuan tertentu atau adanya bukti tertentu. Proses evaluasi dapat dilakukan secara tersendiri terpisah satu dengan yang lain (singular) atau secara komparatif dengan menggunakan acuan tertentu.
Penilaian etis dapat dilihat sebagai keputusan binari seperti benar – salah, etis – tidak etis dan baik – buruk atau sebagai keputusan yang mengandung intensitas yang berkesinambungan. Karakterisitk whistleblower yang terkait dengan etis antara lain adalah whistleblower pada umumnya bersifat altruistis, berintegritas dan merasa bertanggung jawab secara sosial (Greene dan Latting, 2004).
Secara umum, penilaian etis terkait dengan pengambilan keputusan dan intensi whistleblowing dimana seorang whistleblower potensial mengevaluasi pelanggaran yang terjadi sebagai perbuatan etis atau tidak etis berdasarkan persepsi mengenai 1) keadilan dan moralitas, 2) budaya dan tradisi yang menjadi pedoman perilaku masyarakat, dan 3) kontrak sosial yang diakui masyarakat (Reidenbach & Robin, 1990).
Lokus Pengendalian sebagai Moderator
Keterkaitan penilaian etis dengan keputusan whistleblowing dapat dimoderasi oleh lokus pengendalian (Chiu, 2003). Seseorang dengan lokus pengendalian intern mempunyai keyakinan diri yang tinggi dan memandang dirinya sendirilah yang mengendalikan keputusannya sedangkan seseorang dengan lokus pengendalian eksternal mempercayai bahwa nasib, keberuntungan atau kesempatanlah yang menentukan apa yang terjadi pada dirinya (Rotter, 1966, cited in Miceli & Near, 1992).
Keterkaitan tesebut dapat juga di moderasi oleh persepsi terhadap tingkat keseriusan pelanggaran yang terjadi. Semakin serius suatu pelanggaran semakin tinggi pengaruh penilaian etis dengan intensi whistleblowing. Faktor moderasi lain yang mungkin berpengaruh adalah komitmen organisasional. Efek penilaian etis terhadap intensi whistleblowing akan semakin kuat pada pegawai yang mempunyai komitmen organisasional yang tinggi.
Religiusitas
Religiusitas adalah tingkat kedewasaan (maturitas) keimanan seseorang yang mengindikasikan tingkat komitmen & perspektif terhadap hakekat agama dan peristiwa agama. Religiusitas dapat diidentifikasi berdasarkan ketaatannya pada ajaran agama. (Benson, et al., 1993). Religiusitas terdiri dari tiga komponen yaitu mengetahui, merasakan dan melakukan. “Mengetahui” mengacu pada komponen pengetahuan tentang agama dan ajarannya, “perasaan” mengacu pada keterikatan emosional mengenai agama dan “melakukan” terkait dengan afiliasi pada lembaga agama, kehadiran dalam ibadah kolektif dan aktivitas ibadah lainnya (Barnett, et al., 1996).
Ketiga komponen ini dapat diukur dan dinilai dengan menggunakan empat kategori penilaian yaitu kepribadian, sikap, praktek ibadah dan hubungan antar manusia. (Othman & Hariri, 2012). Nilai-nilai Religiusitas mempengaruhi sikap dan perilaku dan persepsi seseorang terhadap whistleblowing maupun dengan intensi whistleblowing (Dozier & Miceli, 1985).
Karakter personal sulit atau bahkan tidak mungkin diubah namun tidak berarti tidak dapat dikelola.
Whistleblowing sebagai salah satu bentuk perilaku pro-sosial organisasional dan sebagai keputusan etis dipengaruhi oleh religiusitas melalui tiga cara yaitu sebagai bagian dari lingkungan kebudayaan, sebagai karakter individu (kepribadian) dan sebagai dasar norma-norma deontologi yang dominan (Hunt & Vitell, 2006).Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap ideology etis dari non-relativisme dan seseorang yang idealistis cenderung ber-whistleblowing (Barnett et al.,1996).
Seseorang dengan tingkat Religiusitas yang tinggi cenderung mengkritik perilaku tidak etis lebih dari orang dengan religiusitas yang rendah. Seseorang dengan tingkat Religiusitas yang tinggi juga cenderung berperilaku etis (O’Fallon & Butterfield, 2005).